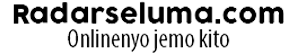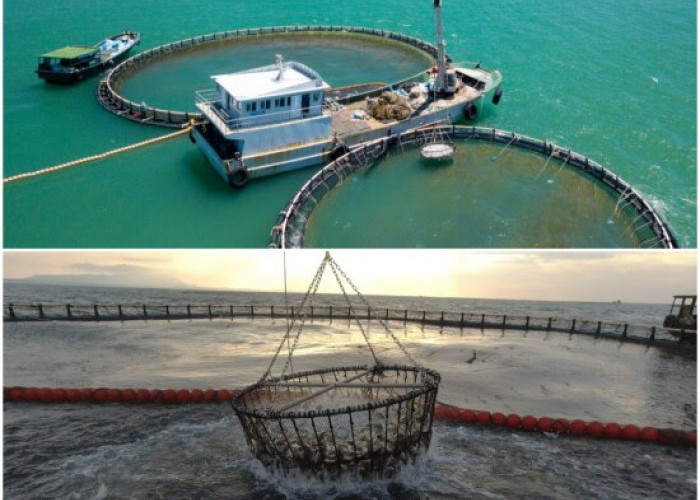Kisah Nyata: Aku Bukan Murahan, Hanya Terpaksa "Di Antara Cahaya dan Luka" Bagian Dua

Radarseluma.disway.id - Aku Bukan Murahan, Hanya Terpaksa "Di Antara Cahaya dan Luka" Bagian Dua --
Reporter: Juli Irawan
Radarseluma.disway.id - Sudah dua minggu sejak pertama kali aku berbicara dengan Arga. Sejak malam itu, rutinitas ku di dunia malam tak lagi sama. Meski tubuhku masih terjebak dalam lingkaran itu, pikiranku mulai bertanya—apa aku masih bisa kembali jadi Sonya yang dulu?
Arga bukan pelanggan biasa. Ia datang hanya untuk duduk, memesan kopi hitam, lalu mengajakku bicara. Ia tak pernah menawar tubuhku. Ia hanya menawar waktu, dengan kesederhanaan yang membuatku merasa manusia lagi. Setiap kata-katanya seperti menarik ku perlahan dari jurang yang selama ini ku tinggali.
"Sonya, kamu tahu nggak?" katanya suatu malam. "Dunia ini memang kejam. Tapi kamu masih bisa memilih mau berdiri di sisi mana."
Aku hanya tertawa pahit. "Kamu kira aku nggak pernah mencoba? Aku pernah, Arga. Tapi dunia lebih cepat menendang ku daripada aku sempat bangkit."
Ia menatapku lama, tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam diam itu, aku merasa didengarkan.
Suatu sore, sebelum kembali bekerja, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak lelah, tapi ada sedikit cahaya di mata yang mulai redup itu. Aku membuka kotak kecil di laci meja rias. Di dalamnya ada kertas-kertas lipat: ijazah SMP, surat dari adik bungsuku, dan foto ibu ketika masih sehat. Aku menatap lama, lalu menangis pelan.
"Aku bukan murahan, Bu... Aku cuma ingin kalian hidup layak. Tapi kenapa jalanku begini?" bisikku lirih.
BACA JUGA:Kisah Nyata: Aku Bukan Murahan, Hanya Terpaksa: Bagian 1 Luka di Balik Senyum
Malam itu, Arga datang lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Ia membawa sebuah map dan satu senyuman yang tak biasa.
"Aku tahu kamu masih punya mimpi," katanya sambil meletakkan map itu di meja. "Aku daftarin kamu ke pelatihan keterampilan perempuan. Ada beasiswa. Kamu bisa belajar, mulai dari awal. Coba aja dulu. Gratis."
Aku menatapnya, terkejut dan bingung. Tak ada pria yang pernah melakukan ini untukku. Mereka biasanya hanya datang untuk mengambil, bukan memberi.
"Kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku.
Ia mengangkat bahu. "Mungkin karena kamu satu-satunya perempuan di sini yang masih bisa menyesal. Dan orang yang masih bisa menyesal... berarti belum sepenuhnya hilang."
Kata-katanya menusuk. Aku menunduk. Malu. Bukan karena profesiku, tapi karena hati yang mulai terbuka untuk harapan.
Beberapa hari setelahnya, aku memutuskan untuk mengambil cuti satu minggu dari tempat kerja. Dengan dalih sakit, aku mulai mengikuti pelatihan itu secara diam-diam. Di sana, aku belajar menjahit dan membuat kerajinan tangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan harapan.
Namun hidup, lagi-lagi, tidak semudah itu.
BACA JUGA:Aktor Andrew Andika Ditangkap Terkait Sabu
Suatu malam, saat aku kembali ke tempat kerja untuk mengambil gaji, aku dipanggil ke ruangan manajer.
“Kamu main belakang, ya? Cari kerjaan lain? Jangan kira kami nggak tahu,” suaranya tajam.
“Aku cuma ambil cuti, Pak. Nggak kerja di tempat lain,” jawabku berusaha tenang.
Tapi dia tidak peduli. “Kamu pikir kamu bisa keluar begitu aja? Kamu laku di sini. Klien-klien suka kamu. Kalau kamu berhenti, kami rugi.”
Aku mulai paham. Dunia ini tak membiarkan siapa pun pergi begitu saja.
“Minggu depan kamu harus hadir. Ada klien VIP yang minta kamu. Kalau kamu tolak, kamu tahu sendiri akibatnya.”
Ancaman itu menusuk seperti pisau dingin di punggungku. Aku keluar dari ruangan dengan napas sesak. Dunia tempatku berdiri saat ini tak hanya gelap, tapi juga penuh jebakan.
Malam itu aku berjalan kaki pulang. Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Aku merasa seperti burung kecil dalam sangkar emas—terlihat bersinar dari luar, tapi di dalamnya penuh luka.
Sesampainya di kontrakan, aku menatap cermin. Wajah itu, mata itu—apa benar ini masih aku?
Teleponku berdering. Arga.
“Aku lihat kamu nggak datang ke pelatihan hari ini. Kenapa?”
Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, “Aku... diancam, Ga. Kalau aku berhenti kerja, aku bisa disakiti. Mereka bilang aku nggak bisa keluar begitu aja.”
Arga tak langsung menjawab. Tapi aku bisa merasakan amarah tertahan dalam napasnya.
“Aku akan bantu kamu keluar,” katanya akhirnya. “Tapi kamu harus siap. Karena saat kamu mulai melawan, mereka pasti akan balik menyerang.”
Aku meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tahu aku tidak sendiri.
Dan malam itu, aku mengambil keputusan. Ini bukan soal pekerjaan lagi. Ini soal martabat. Soal hakku sebagai manusia untuk memilih jalan sendiri.
Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi jika cahaya kecil di hatiku masih menyala, aku harus menjaganya. Sebab aku bukan milik dunia malam ini. Aku milik diriku sendiri. Dan aku berhak bahagia. (djl)
Bersambung ke Bagian 3…
Sumber: