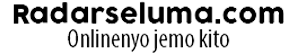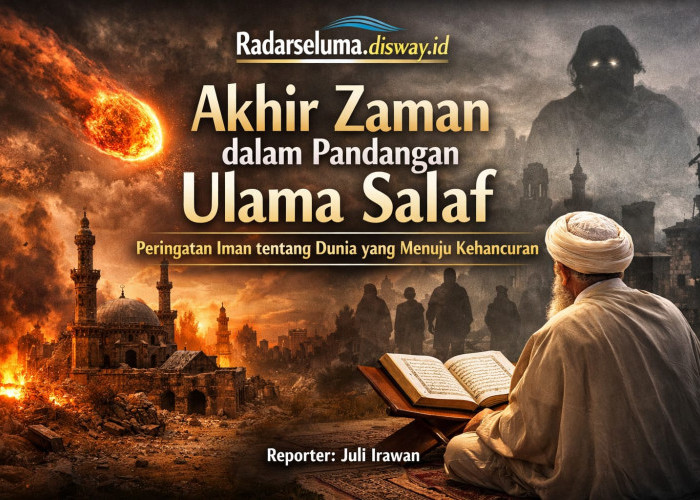Kisah Nyata: Hutang Keluarga Menjerumuskan Ku “Awal dari Semua Beban” (Bagian 1)

Radarseluma.disway.id - Kisah Nyata: Hutang Keluarga Menjerumuskan Ku “Awal dari Semua Beban” (Bagian 1) --
Reporter: Juli Irawan
Radarseluma.disway.id - Namaku Nisa. Aku perempuan biasa, 22 tahun, baru saja lulus dari sebuah universitas swasta di Jakarta dengan gelar Sarjana Manajemen. Seperti banyak anak muda lainnya, aku punya mimpi bekerja di perusahaan ternama, membahagiakan orang tua, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi hidup tak selalu seperti yang direncanakan.
Sebelum pandemi, keluarga kami hidup sederhana. Ayah memiliki usaha konveksi kecil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Ibu adalah ibu rumah tangga sepenuh waktu, dan aku punya dua adik laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah. Hidup kami mungkin tidak mewah, tapi hangat. Setiap malam kami makan bersama, saling bercerita, dan tertawa walau sederhana.
Semua berubah ketika pandemi datang. Usaha Ayah gulung tikar. Pelanggan berhenti memesan, bahan baku naik, dan perlahan satu per satu karyawan harus dirumahkan. Aku masih ingat bagaimana Ayah berusaha menenangkan kami, berkata bahwa ini hanya sementara. Tapi hari demi hari, tagihan listrik, air, sekolah adik-adikku, dan cicilan rumah terus berdatangan. Tak ada pemasukan. Ayah mulai meminjam uang dari bank. Ketika itu tak cukup, beliau terpaksa meminjam dari rentenir.
BACA JUGA:Kisah Nyata: Aku Bukan Murahan, Hanya Terpaksa: Bagian 1 Luka di Balik Senyum
Hari itu masih sangat jelas dalam ingatanku. Malam yang muram, hujan turun perlahan, dan Ayah pulang dengan langkah berat. Wajahnya lelah, mata sembab. Kami duduk di ruang tamu dalam diam. “Kita harus siap-siap pindah dari rumah ini,” katanya pelan. Ibu langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Aku melihat adik-adikku terdiam, tidak mengerti, tapi jelas mereka merasa ketakutan. Rumah kami akan disita.
Sebagai anak sulung, hatiku tercabik. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku mulai menyebar lamaran kerja ke mana-mana. Aku rajin membuka portal lowongan pekerjaan setiap hari, dari posisi admin, customer service, bahkan pekerjaan paruh waktu. Tapi di tengah ribuan pencari kerja yang juga terjebak krisis, ijazahku terasa tidak ada harganya. Beberapa kali aku dipanggil wawancara, tapi selalu berujung penolakan. Aku bukan siapa-siapa. Tidak punya pengalaman, tidak punya koneksi, hanya anak biasa dari keluarga biasa.
Dalam keputusasaan itu, aku melihat unggahan di Instagram dari Lela, teman semasa kuliah. Dulu dia cukup populer, orang-orang suka padanya. Tapi kini dia tampak berbeda—lebih cantik, glamor, sering berfoto di hotel bintang lima, dengan barang-barang bermerek di tangannya. Aku memberanikan diri menghubunginya lewat DM, bertanya kabar, dan menyampaikan bahwa aku sedang mencari pekerjaan.
“Ketemu yuk, ngobrol langsung aja,” balasnya cepat. Kami janjian bertemu di sebuah kafe mewah di daerah Senopati. Aku hampir ragu datang ke sana, merasa minder dengan pakaianku yang lusuh dan wajah yang tak sempat kutata. Tapi aku tetap pergi, demi harapan.
BACA JUGA:Kisah Nyata: Aku Bukan Murahan, Hanya Terpaksa
Lela muncul dengan penampilan mencolok. Make-up-nya rapi, tubuhnya wangi, dan sebuah tas branded menggantung manis di lengannya. Kami ngobrol basa-basi sejenak, sebelum aku akhirnya bertanya, “Kerja apa, Lel?”
Dia menatapku sebentar, lalu menjawab, “Freelancer. Tapi bukan yang kamu bayangin. Aku bantuin klien-klien penting, nemenin mereka di acara atau perjalanan. Dibayar mahal. Bisa atur jadwal sendiri.” Ia bicara santai, seolah itu hal biasa.
Aku tidak bodoh. Aku tahu apa maksudnya. “Kayak... teman kencan gitu?” tanyaku hati-hati. Dia mengangguk ringan. “Kurang lebih. Tapi gak harus ngelakuin semuanya. Tergantung kamu. Yang penting tetap tahu batas.”
Hatiku terasa ditusuk. Aku tahu jalan itu bukan yang seharusnya. Tapi ketika Lela menambahkan, “Aku juga dulu cuma mau bantu keluarga. Gak semua orang lahir dengan kemewahan. Kadang kita cuma bisa bertahan dengan cara yang gak ideal,” aku terdiam.
Aku pulang dengan hati berkecamuk. Di dalam kamar, aku termenung, memikirkan betapa dunia ini tidak adil. Aku ingin tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan orang tuaku. Tapi realita memaksaku berpikir ulang. Saat malam itu aku melihat adik bungsuku menangis karena perutnya kosong dan Ibu terisak diam-diam di dapur karena tak mampu membeli beras, aku merasa seolah tenggelam dalam lumpur tanpa tali.
Malam itu aku tak bisa tidur. Hatiku hancur. Tapi keesokan harinya, dengan jari gemetar, aku membuka ponsel dan mengetik pesan pada Lela: “Aku siap. Tapi cuma untuk satu kali.”
Kupikir itu hanya sekali. Tapi itulah awal dari semuanya. (djl)
(Bersambung ke Bagian Dua)
Catatan: Cerita ini adalah potret nyata tentang kerasnya kehidupan dan tekanan ekonomi yang bisa menyeret siapa saja ke jalan yang salah. Namun, ia juga menggambarkan kekuatan tekad, keberanian untuk berubah, dan arti penting dari pengampunan. Karena di balik setiap kesalahan, selalu ada ruang untuk kembali.
Sumber: